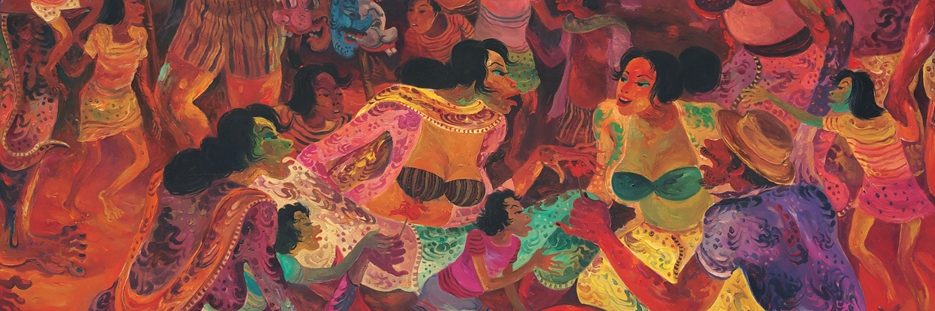Sanata Dharma. Enam puluh tahun universitas kita genap berusia. Enam puluh tahun Sanata Dharma mendidik ribuan mahasiswa dari berbagai penjuru Indonesia. Mari sedikit berhitung: universitas kita menerima kurang lebih dua ribu mahasiswa setiap tahunnya. Anggaplah jumlah itu sebagai nilai rata-rata penerimaan mahasiswa baru dari tahun ke tahun, maka 60 x 2.000 = 120.000 mahasiswa. Kecil? Mungkin. Seratus dua puluh ribu bukanlah angka yang besar bila dibandingkan dengan dua ratus lima puluh juta penduduk Indonesia, namun mari kembali berhitung: bila satu orang lulusan mendidik lima orang saja, dan lima orang itu mendidik lima orang yang lain, maka lebih dari satu juta orang merasakan buah pendidikan Sanata Dharma. Belum lagi lulusan yang berprofesi sebagai guru, dan sebagaimana kita ketahui, FKIP merupakan fakultas terbesar di universitas kita. Maka tak salah jika kita menyatakan bahwa enam puluh tahun Sanata Dharma mendidik Indonesia. Sebuah pengabdian yang luar biasa bagi negeri kita yang tercinta.
Saya telah mengajak Anda sekalian untuk berhitung bersama-sama, mengkalkulasi kemungkinan besarnya peran universitas kita di tengah kompleksnya problematika dunia pendidikan di Indonesia; distribusi pendidikan yang tidak merata, siswa didik yang menjadi korban eksperimentasi kurikulum, pendidikan yang (masih) berorientasi pada mencetak tenaga kerja buruh (buruh, yang saya angkat dalam arti luas sebagai pegawai dalam bidang apapun dan bukan majikan; guru pun tergolong sebagai buruh pendidikan) dan bukan pencipta kerja, pembunuhan daya imajinasi siswa dalam konformitas sistem pendidikan yang ada, dsb. Hitungan di atas memang masuk akal ketika kita mengumpamakan bahwa seluruh mahasiswa lulusan Sanata Dharma adalah seorang pendidik. Namun benarkah demikian? Apakah identitas dan jati diri pendidik sungguh-sungguh melekat pada diri pribadi setiap mahasiswa di bidang apapun yang mereka ampu? Sudahkah Sanata Dharma, sebuah universitas dengan nilai 3C (Competence, Conscience, Compassion) dan motto Cerdas dan Humanis yang sangat dibanggakan oleh civitas akademika yang ada di dalamnya, sungguh-sungguh menanamkan identitas dan jati diri pendidik dalam diri setiap mahasiswanya?
Pendidikan: sebuah identitas
Driyarkara, pendiri universitas kita, menyatakan: pendidikan adalah sebuah proses yang menjawab problem eksistensialisme. Pendidikan menjadikan manusia sebagai seorang manusia yang utuh, menjadikan manusia itu sendiri menjadi seorang manusia; sebuah proses yang oleh Driyarkara disebut sebagai proses hominisasi. Hal ini merupakan sebuah proses di mana seorang manusia memanusiakan manusia lain yang ada di sekitarnya. Seekor kerbau mengkerbau dengan sendirinya, namun manusia tidak bisa memanusia dengan sendirinya. Dia butuh manusia lain untuk memanusiakan dirinya; sebuah proses yang disebut sebagai proses humanisasi. Semua itu terjadi dengan tujuan memanusiakan manusia secara utuh, memberikan manusia daya yang membuat dirinya menjadi manusia: akal budi, hati nurani, kehendak bebas, serta ilmu pengetahuan, dan menjadikan dirinya berguna bukan hanya untuk dirinya sendiri, melainkan pula manusia-manusia lain yang ada di sekitarnya.
Pendidikan melekat erat dalam identitas Sanata Dharma sebagai sebuah universitas. Sejarah mencatat Sanata Dharma menyandang status Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) pada awal berdirinya di tahun 1955 hingga tahun 1958, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP) pada tahun 1958 hingga tahun 1965, Institut Keguruan Ilmu Pendidikan (IKIP) pada tahun 1965 hingga tahun 1993, hingga akhirnya menyandang status Universitas pada tahun 1993 hingga saat ini. Saat itu mulai muncul berbagai fakultas dan program studi yang baru di Sanata Dharma, mulai dari fakultas Psikologi hingga fakultas Sains dan Teknologi. Meski demikian, identitas pendidik tak akan pernah lepas dari Sanata Dharma, terlebih dengan pendidikan yang berorientasikan pada visi ‘memanusiakan manusia muda’. Competence, conscience dan compassion pun menjadi tiga nilai dasar pendidikan di Sanata Dharma sebagai universitas Jesuit. Mahasiswa dididik dalam mengasah kompetensi, menyadari segala daya dan kemampuan yang ada padanya, dan mengaktualisasikannya dalam aksi yang nyata bagi sesama. Akan tetapi, sudahkah pendidikan di universitas kita sungguh sampai pada nilai compassion? Sudahkah mahasiswa dididik untuk mengimplementasikan ilmu yang mereka miliki dalam aksi yang nyata di tengah masyarakat? Ataukah pendidikan di universitas ini berhenti pada nilai conscience saja, bahkan lebih memprihatinkan lagi, competence yang lumpuh dan bisu?
USD Mengajar
Saya terinspirasi oleh seorang tokoh pendidikan dewasa ini: Anies Baswedan. Beliau sungguh merupakan sosok seorang pendidik yang membumi. Beliau tak hanya berhenti pada ruang diskusi publik macam seminar pendidikan yang mengusung tema keprihatinan dan problematika pendidikan di Indonesia; lebih dari itu, beliau menggagas dan menginisiasi sebuah gerakan yang secara nyata menjawab berbagai keprihatinan dan problematika tersebut: Indonesia Mengajar. Gerakan ini berangkat dari keprihatinan Anies akan ketidak-merataan pendidikan di Indonesia, di mana tidak semua orang mengenyam pendidikan yang layak. Dimulai pada tahun 2009, gerakan ini mendapat atensi yang sangat tinggi dari publik. Ribuan orang rela mendaftar untuk menjadi bagian dari Pengajar Muda demi memenuhi janji kemerdekaan: mencerdaskan kehidupan bangsa. Kini Pengajar Muda telah sampai pada angkatan X dan tersebar di berbagai pelosok tempat di Indonesia, berjuang memenuhi janji kemerdekaan tersebut.
USD Mengajar terinspirasi dari gerakan Indonesia Mengajar. Gerakan ini berawal dari keinginan untuk mengembalikan kesadaran akan identitas dan jati diri mahasiswa Sanata Dharma sebagai seorang pendidik serta pentingnya karya nyata di tengah masyarakat sebagai aktualisasi nilai compassion sebagai puncak dari nilai 3C. Gerakan ini tidak terbatas pada pendidikan formal akademik, melainkan pula pendidikan non formal dan non akademik: mahasiswa Sastra Inggris mengajar ibu-ibu PKK, mahasiswa Teknik Mesin boleh mengajar cara membuat kincir angin, mahasiswa Psikologi boleh mengajar anak-anak berkebutuhan khusus, dsb. Gerakan ini melampaui batas pendidikan dalam lingkup formal-akademik, serta mengangkat pendidikan sebagai bagian dari proses kemanusiaan itu sendiri; sebuah proses memanusiakan manusia.
Sejumlah orang mengkritik gerakan ini sebagai sebuah gerakan yang kecil dan tidak berdampak; USD Mengajar tersebar di delapan belas titik di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan dilakukan hanya dalam jangka waktu empat puluh hari. Gerakan ini pun dinilai membebek dan tidak orisinil. Meski demikian, sekecil apapun dampak yang muncul daripadanya, gerakan ini telah membantu mahasiswa Sanata Dharma yang terlibat di dalamnya dalam menghidupi nilai-nilai humanisme serta identitas dan jati diri pendidik yang melekat erat pada identitas Sanata Dharma. Mereka telah berkarya nyata di tengah masyarakat dalam proses memanusiakan manusia muda, suatu karya yang sungguh luar biasa dan sangat erat dengan janji kemerdekaan bangsa ini: mencerdaskan kehidupan bangsa.
Kepada segenap panitia dan volunteer USD Mengajar: Anda luar biasa. Anda sangat beruntung menjadi angkatan pertama USD Mengajar. Semoga USD Mengajar menjadi sebuah program berkelanjutan di universitas kita, berlanjut pada USD Mengajar angkatan II, angkatan III, angkatan IV, dan seterusnya, serta meluas ke berbagai pelosok, tak hanya di Yogyakarta, melainkan di seluruh Indonesia.
100% Cerdas, 100% Humanis.
Sleman, 26 April 2015
Andreas Rahardjo Adi Baskoro
Presiden BEM Universitas Sanata Dharma
Kabinet USD Menyala